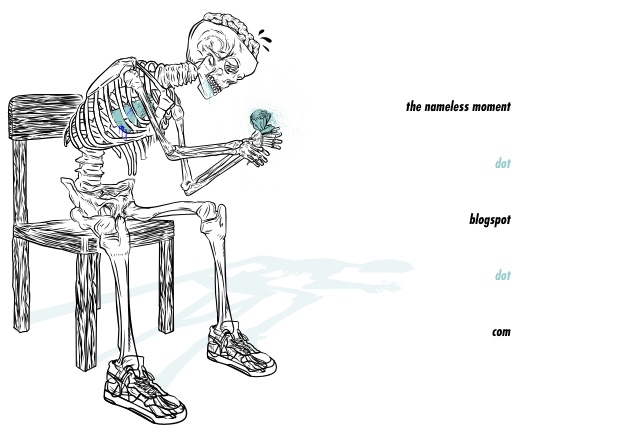Wednesday, December 17, 2008
Saturday, December 13, 2008
Akhir-Akhir Ini Acara Televisi Asyik Sekali

Hari ini Bapak dan Ibu mengajak aku menonton televisi di kelurahan setelah dua minggu lamanya kami hanya mendengarkan radio di rumah. Di sana kami menyaksikan sebuah tayangan sinetron. Ada orang yang berubah jadi ular, naga, dan buaya. Lalu lainnya terbang ke awan, berkelahi di sana. Karena masalah memperebutkan perempuan sih sepertinya. Kadang-kadang mereka berbicara, tapi terdengar seperti bukan suara mereka. Aneh sekali. Mungkin TV di kelurahan kami sedang rusak. Ah apapun itu, aku, Bapak, dan Ibu tidak peduli karena sinetron yang kami tonton itu sungguh mengasyikan. Tidak terlalu banyak iklannya. Bahkan tidak ada. Bapak dan Ibu benci iklan. Membuat aku rewel, katanya.
Tiba-tiba, ada seseorang yang memindahkan sinetron itu ke sebuah acara yang menampilkan seorang wanita yang menangis-nangis di sebuah tempat. Wah baru sebentar menonton adegan menangis itu, acara sudah terpotong. Iklannya banyak sekali. Yah.
Acara dimulai lagi, wanita itu masih menangis. Dia hamil katanya. Pacarnya kabur. Pacar itu kan yang biasa dipakai ibu untuk mencat kuku. Pacar cina, kan. Apa pacarnya digondol kucing ?. Kenapa dia menangis ?. Mana suaminya bukannya dia sedang hamil ?.
Sekarang wanita itu ada di rumah sakit. Dia sedang menengok seorang lelaki. Sudah dicari-cari sejak dulu katanya. Begitu wanita itu bilang dia hamil, lelaki itu meninggal. Mereka bilang itu pacarnya. Pacar itu ternyata seorang lelaki toh.
Lho, lalu apa yang dipakai ibu untuk mencat kuku ? Apa berarti ia dibantu seorang lelaki ?. Bukankah itu tidak baik ? Apa hal ini harus kulaporkan pada Bapak ?. Tapi Bapak tampak tidak peduli. Lagipula Bapak pintar, lebih pintar dari aku, pasti lebih mengerti. Lebih baik aku lanjutkan menonton TV. Selagi kami masih di sini.
Sinetron ini berbeda dengan yang sebelumnya kami tonton. Tidak ada silat dan hewan-hewan menakjubkan seperti naga dan capung raksasa. Hanya ada orang menangis dan pertengkaran. Di rumah sakit kok menangis dan bertengkar ? Ini sinetron apa ya ?. Bapak bilang, ini nyata. Oh aku baru tahu televisi menampilkan hal-hal yang nyata. Jadi naga itu ada ya. Kapan ya aku bisa menaiki capung bersama dengan 3 putri kahyangan ?. Apa itu hanya ada di televisi ?. Kalau begitu, aku juga ingin ditayangkan di televisi. Aku harus jadi artis televisi agar bisa mewujudkan impianku untuk bertemu makhluk-makhluk ajaib itu. Asal aku tidak perlu menangis dan bertengkar di depan orang yang baru saja meninggal seperti sinetron yang sedang kami tonton ini. Eh bukan sinetron, ini nyata kata Bapak.
Wednesday, December 10, 2008
SORGE by Media Parahyangan

Siang itu sekitar pukul duabelas, beredar sebuah selebaran yang diedarkan teman saya, Acong, dari Media Parahyangan Unpar. Sebuah bulletin, ternyata. Mempertanyakan eksistensi Ikatan Alumni.
Sedikit gambar grafis goretan tangan di tengah kertas : Para pelamar kerja yang antri berurutan di depan pintu dihadapkan pada seorang sekretaris wanita yang berkata, “Para alumni unpar silakan langsung memanjat tali ini ke atas.” Tangan wanita itu menunjuk pada seutas tali yang tampaknya terikat pada suatu pasak entah di lantai berapa, melewati sebuah lubang ada atap tepat di atas kepala para pelamar tersebut. Mereka terbengong-bengong.
Setelah membaca wacana yang tertulis pada buletin tersebut, saya baru mengerti arti dari gambar yang absurd itu. Multi-interpretasi, pikir saya.
Kesampingkan dulu sajalah masalah itu.
Waktu sore di hari yang sama. Saya dan beberapa teman saya masih sabar menunggu sebuah acara dengan duduk-duduk di salah satu tempat di Unpar yang saya lupa namanya. Saat itu hujan, saya sangsi acara ini akan dimulai tepat waktu. Menurut jadwal yang tercetak pada pamflet, acara tersebut seharusnya dimulai pada jam 18.30 WIB. Saya terus menunggu hingga akhirnya lewat waktu Maghrib Acong mengajak kami pergi menuju Student Center (SC).
Wah, ternyata acara sudah dimulai begitu kami sampai di sana. Saya heran. Tepat waktu tampaknya sudah menjadi hal yang terlalu aneh bagi saya, mungkin juga bagi banyak orang lainnya. Sudahlah, saya kira itu tidak perlu diperbincangkan.
Sorge, sebuah acara komunitas yang dipersembahkan Media Parahyangan, adalah salah satu bukti keberhasilan prinsip DIY dalam penyelenggaraan sebuah event. Ketidakberadaan sponsor tidaklah menjadi sebuah masalah yang berarti ketika hubungan pertemanan masih sangat bisa diandalkan. Semua yang tampak di sana, amplifier, drum, cabinet, dan sebagainya adalah hasil sumbangan bantuan dari teman-teman komunitas unpar dan lainnya. Seminggu sekali, harapan si MC tentang frekuensi penyelenggaraan event seperti Sorge ini. Dito, nama MC itu, sesekali menyinggung tentang rekannya yang tengah berada di PvJ. Seharusnya rekannya itu menjadi partner dia dalam membawakan acara, katanya. Pantas saja dia banyak ngelantur ga jelas ke sana sini walau memang kadang pembicaraannya mengundang tawa banyak orang. Hahaha. Kemudian dia lanjut berbicara tentang PvJ. Terus tentang PvJ.
Sayup-sayup dari kejauhan terdengar bunyi orang berkaraoke. Suara itu bersumber dari acara temu alumni fakultas hukum unpar yang sudah diselenggarakan sejak pagi/siang tadi. Tiba-tiba saya teringat tentang perkataan teman saya perihal adanya mobil Ferrari dll di pelataran parkir. Kabarnya kendaraan tersebut milik orang-orang yang hadir pada acara temu alumni. Sungguh ironis bila dikaitkan dengan buletin yang saya baca pada siang harinya. Ketika kesuksesan hanya menjadi milik sendiri, maka apalah guna ikatan alumni. Bubarkan saja dan ludahi lambang perkumpulan itu. Mungkin mereka tidak pernah mengadakan atau sekedar ikut menonton acara-acara seperti Sorge yang amat kental nuansa solidaritasnya. Hingga mereka lupa bahwa di balik semua keberhasilan mereka, tersimpan jasa-jasa orang lain yang tidak mungkin tergantikan oleh kompensasi materiil yang telah mereka dapatkan.
Pikiran-pikiran di atas saya simpan di hati tanpa saya muntahkan sedikitpun saat itu. Buat saya, menyaksikan kelanjutan acara ini lebih menguntungkan dibandingkan membuang-buang tenaga untuk memikirkan orang lain.
Tuesday, December 09, 2008
Segelas Es Batu dan Listrik yang Tidak Boleh Diambil
Akhirnya terlihat juga bentuk asli dari minuman itu. Tapi mulut saya sudah keram akibat terlalu banyak memakan es batu. Saya kesampingkan dulu gelas itu lalu kembali berkonsentrasi pada laptop saya.
Oh. Saya kegeeran. Saya bukan anak yang shaleh. Tuhan tidak sebegitu sayangnya pada saya hingga akhirnya saya sadar di atas steker itu ada stiker yang menempel dan berbunyi : “BUKAN UNTUK UMUM. INTERNAL USE ONLY”.
Saya berpikir. Saya telah membeli segelas minuman : yang tidak tampak seperti minuman. Daripada saya mengadukan masalah es batu yang kebanyakan ini ke Surat Pembaca Pikiran Rakyat, lebih baik BSM membiarkan saya mencolokkan steker laptop saya ke tiang itu. Itu kompensasi yang masuk akal, pikir saya. Tapi tentu saya tidak mau menanggung malu dengan sok percaya dirinya menggunakan sesuatu yang tidak seharusnya digunakan seenaknya. Di sana banyak orang. Di depan saya, samping kiri dan samping kanan. Dan saya juga yakin mereka bisa membaca tulisan yang tercetak di stiker itu.
Tutup saja stikernya !. Haha! Ide itu terlintas. Saya tidak perlu malu seandainya mereka tidak tahu bahwa colokan itu bukan untuk umum. Lalu saya ambil secarik tisu, saya basahi dengan sedikit air dari minuman saya itu kemudian saya tempel pada stiker tersebut. Oh, orang-orang itu melihat tindakan saya dan mulai mencibir dengan matanya yang sinis. Biarlah.
Wahaha. Akhirnya saya bisa juga internetan sepuasnya.
Beberapa menit kemudian , datang lelaki berbadan besar dengan seragam abu-abu ke sebelah kanan saya.
Wah, ada apa ini. Jangan-jangan dia mau mengajak berkenalan. Saya bukan homo hei.
Tak lama kemudian, laptop saya mati.
. . .
Sial, sekarang saya justru lebih berharap dia datang untuk mengajak berkenalan agar saya tetap bisa menggunakan fasilitas wi-fi gratis itu di sana. Malunya saya hari itu. Segelas minuman, eh maaf, segelas es batu, tatapan sinis dari orang di sana, teguran satpam, uang yang terbuang percuma.
Lebih baik minuman ini saya jual lagi ke warnet, ditukar dengan jatah main selama 2 jam.
Sunday, December 07, 2008
Mama Left When The Sun is Rising Up
Saat itu, saya tanpa sengaja bertemu dengan guru saya semasa SMP, sebut saja Ibu XXX. Sebenarnya kata ‘bertemu’ di sini kurang relevan bila dikorelasikan dengan bentuk pertemuan itu sendiri. Saya hanya melihat beliau tanpa menyapa bahkan tersenyum pun tidak. Saya juga ragu-ragu saat mencoba mengenali beliau karena memang perawakan dan penampilannya agak sedikit berbeda. Tidak mungkin sesederhana ini, pikir saya begitu melihat cara beliau berpakaian mengingat profesinya sebagai seorang guru di SMPN 2 Bandung, sekolah yang memang - entah kenapa – meninggalkan banyak kesan hedonis di ingatan saya. Ditambah lagi pada waktu itu Ibu XXX menggandeng seorang anak sambil beberapa kali menyuapinya dengan makanan dari kotak bekal yang ada di sebelah tangannya.
Mama. Begitu dia sebut dirinya di depan anak itu. Setahu saya, Ibu N’deu sudah terlalu tua untuk memiliki anak seumur itu. Bahkan hal itu tidak lazim seandainya hal itu terjadi 6 tahun lalu saat saya masih belajar padanya. Saya sempat berpikir, dunia berubah begitu cepat dalam setengah dekade. Dan waktu berlalu begitu saja tanpa ada peringatan jelas dari Tuhan tentang banyaknya waktu yang saya sia-siakan. Lamunan itu lantas buyar begitu mendengar kalimat sapaan dari orang di sebelahnya yang sudah sejak sebelumnya mengamati tingkah laku si anak yang memang agak sedikit lincah ke sana ke mari.
“Sabaraha taun (berapa tahun), Bu ?”
“Tilu taun, tapi kirang bentes ieu mah ngomongna. Nu putri mah lancar. Kembar ieu teh. (Tiga tahun, tapi kurang lancer ini bicaranya. Yang perempuan sih lancar. Kembar.”
Kembar ?. Beliau pasti bercanda. Melihat anak kecil itu saja saya sudah terheran-heran.
“Ohh, bodas nya. Meni kasep. (Ohh, putih ya. Ganteng)”
“Muhun, beda jeung nu hiji deui mah perempuan. Hideung, terus rada gendut. (Iya, beda sama yang perempuan. Item, sedikit gendut)”
“Anak, Bu ?”
(berbisik) “ Lain, anak angkat. Ti saminggu. Indungna kabur. Bapana teuing dimana. Nini na ge teu paduli rek kumaha. Lain urusan cenah.(Bukan, anak angkat. Dari umur seminggu. Ibunya kabur, Ayahnya ga tau dimana. Neneknya juga ga mau tahu. Bukan urusan dia katanya)”
. . .
Benar ternyata, dunia berubah di luar apa yang pernah saya bayangkan sebelumnya. Bahkan, percakapan itu pun secara tidak langsung telah meubah pemikiran saya beberapa detik sebelumnya tentang kejanggalan akan keberadaan anak itu, yang semula rasa heran menjadi rasa kasihan. Dari lontaran demi lontaran kata yang terlempar dari mulut mereka, saya menangkap – setelah menguping – sebuah pembicaraan tentang anak kembar yang terbuang, ibu yang kabur meninggalkannya, dan ayah yang tidak bertanggung jawab, juga seorang nenek yang tidak mau peduli perihal kelahiran penerusnya itu. Memang semua tidaklah murni kesalahan mereka, tapi seharusnya ada rasa peduli dan tanggung jawab karena sedikit banyak mereka telah terlibat di dalamnya. Kita adalah manusia. Dan manusia tidak pernah memiliki hak untuk membatasi masa hidup orang lain dengan membiarkan sepasang anak yang baru lahir terabaikan begitu saja seperti bongkahan batu di halaman.
Entah bagaimana perasaan yang akan timbul di hati anak-anak itu begitu dewasa nanti. Tak ada garis muka yang mampu menggambarkan sedikit saja wajah orang tua mereka di rumah saat bercermin. Keheranan akan jauhnya umur mereka dengan orang tua mereka. Ketidaklaziman golongan darah dari garis keturunan. Akan selalu ada pertanyaan yang hinggap sebelum mereka tertidur lelap : tentang eksistensi mereka. Mungkin saja pertanyaan-pertanyaan itu suatu hari akan mengantarkan mereka memilih jalan untuk tertidur lelap selamanya sebelum tiba saat yang seharusnya.
Biar saja ia jatuh ke sungai, biar saja ia terberai berantakan, biar saja ia diguyur hujan.
Entah burung apa itu hinggap di batang pohon akasia, janggal.
Kulempar dengan sebongkah batu di halaman.
Selama ini, dunia telah mengubah banyak orang kembali menjadi manusia purba dengan aturan hidup a la hutan rimba. Kita terlalu banyak mendongakkan kepala ke arah televisi hingga lupa cara menunduk dan membungkuk. Kita terlalu banyak berempati pada Aqso dan Madina, tapi lantas melupakan nasib ribuan anak jalanan yang dipekerjakan sebagai pengemis oleh oknum-oknum keparat. Kita gunakan kartu debit dan kredit sebagai alasan ketidakhadiran uang recehan untuk disumbangkan kepada mereka yang malang di pelataran jalan sana.
Membuang muka dan menyembunyikan tangan mungkin telah menjelma menjadi Pancasila baru di muka bumi Indonesia ini. ‘Rasa peduli’ sudah saatnya dipajang dalam lemari-lemari tua di museum. Dikenang. Tanpa pernah dirasakan.
Saturday, December 06, 2008
Thursday, December 04, 2008
Mono & World's End Girlfriend : Palmless Prayer / Mass Murder Reffrain

Begitu mendengar seputar EP kolaborasi Mono & World's End Girlfriend, saya sekejap dihantui rasa penasaran akan seperti apa jadinya. Dan akhirnya saya mendapatkan sebuah link yang mengantarkan saya untuk men-download EP ini secara ilegal. Iya, saya minta maaf. Salahkan pemerintah yang tidak mengerti kegelisahan anak muda yang tidak punya banyak uang tapi butuh hiburan di waktu senggang. Seandainya pajak barang-barang seperti ini diturunkan, tentu saya akan memilih untuk membeli CD yang asli. Oh, jadi ngelantur ke mana mana.
Kover album ini mengingatkan saya pada satu situasi di sebuah komik , Monster, tentang sebuah pintu rahasia yang terbongkar setelah sekian lama tertutup oleh tembokan beton di mana di dalamnya terkubur puluhan tengkorak korban pembunuhan massal yang terjadi puluhan tahun lalu. Ada sedikit korelasi memang antara cerita tersebut dengan judul dari EP ini, Palmless Prayer/Mass Murder, tapi saya tidak yakin Takaakira Goto sengaja membuat EP ini karena membaca komik itu. Yah, sedikit mengkhayal boleh lah.
EP ini berisi sebuah lagu yang terpotong-potong menjadi 5 bagian dengan total durasi 1 jam 19 menit , sehingga album ini tidak direkomendasikan bagi mereka yang biasa mendengar musik jenis tweepop . Menyimak album ini sungguh melelahkan. Komposisi gabungan antara strings, choir yang sedikit mistis, piano-type, dan gemuruh musik Mono kadang dirasa sedikit over ditambah dengan durasi yang terlalu panjang. Tapi, mungkin memang itulah yang dicari oleh mereka selama ini : musik orkestrasi avant-garde era kontemporer. Setidaknya itu yang bisa ditangkap bila melihat dari ciri musik mereka, khususnya World's End Girlfriend. Lalu, saya berpikir seandainya mereka mampu memainkannya secara live mungkin akan banyak wanita di luar sana yang menangis sesudahnya. Oke, memang terlalu berlebihan. Tapi, memang tidak pernah ada tone 'bahagia' yang terkandung pada lagu-lagu mereka, baik di EP ini maupun di album-album mereka sebelumnya. Terlalu gelap, teman saya bilang saat saya merekomendasikan band-band ini padanya.
Overall, album ini adalah sebuah karya yang pantas dikoleksi. Simpanlah dulu uang yang sudah kalian kumpulkan untuk membeli album d'Masiv atau Seventeen. Coba dengarkan musik dari negeri jepang sana dan segera beli gitar sekaligus efeknya lalu buatlah musik yang lebih hebat.